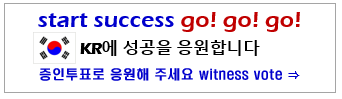Cerita Pendek | Ketika Cinta Memilih Pergi
Senja merayap di tepian kota. Gerimis tipis yang turun tiba-tiba membungkus jalanan. Cahaya lampu melahirkan warna keemasan yang tampak memudar. Di pojok taman Riyadah -- satu-satunya taman di kota itu -- Andra duduk sendiri. Matanya menatap lekat salah satu bayangan pepohonan. Angin sore berhembus lembut, seolah ingin menghibur hati yang patah. Namun suasana yang hadir ketika itu justru menambah sepi dan menusuk dadanya.
Ia rindu Nayla. Terbayang betapa bahagianya ia selama ini. Hidupnya penuh tawa. Ketika setiap detik bersama Nayla, adalah surga yang ia genggam erat. Selama ini, mereka begitu dekat, begitu lekat, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Setiap senyum Nayla adalah cahaya, setiap sentuhannya adalah rumah. Andra tak pernah membayangkan akan ada hari di mana semua itu berubah menjadi luka.
Andra memejamkan mata. Ia membiarkan kenangan itu datang di alam pikirannya. Mereka dulu tak pernah berpikir tentang akhir. Hidup hanyalah tentang hari ini, tentang mencintai dengan segala keberanian. Hingga suatu hari, keberanian itu berubah menjadi kerapuhan.
Semua bermula dari hal kecil. Pesan yang tidak dibalas. Janji yang terlupakan. Perhatian yang pelan-pelan memudar. Andra mencoba menguat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Tapi setiap kali Nayla mengabaikannya, ia merasa seperti karang yang terus dihantam ombak, retak sedikit demi sedikit.
Ia bertahan. Karena cinta, ia bertahan. Seperti orang bodoh, ia terus percaya meski hatinya diremukkan berkali-kali. “Ini hanya badai kecil,” begitu ia selalu membatin. Namun badai itu tak kunjung reda, justru berubah menjadi topan yang meluluhlantakkan keyakinannya.
Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari ketika Andra melihat Nayla berjalan bergandengan dengan pria lain. Senyum yang dulu hanya miliknya, kini terukir di wajahnya untuk orang lain. Dunia Andra runtuh seketika. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya sunyi. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu—ini bukan lagi soal siapa salah, siapa benar. Ini tentang sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia genggam lagi meskipun seluruh tubuhnya meronta untuk mempertahankannya.
Ia mencoba menghapus jejak Nayla dari hidupnya, tapi setiap sudut kota bercerita tentang mereka. Bangku taman tempat ia duduk sekarang adalah saksi tawa mereka. Lampu jalan yang mulai menyala malam ini mengingatkannya pada malam-malam mereka berjalan berdua, menggenggam tangan erat seakan dunia tak mampu memisahkan.
Andra menghela napas berat. “Sampai kapan aku harus menanggung ini?” gumamnya lirih. Rasanya seperti kutukan. Cinta yang dulu indah kini berubah menjadi beban yang menghimpit dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia ingin bebas, tapi bayangan Nayla terus menghantui.
Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tak asing—Nayla. Jemarinya bergetar saat membuka pesan itu. “Bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang harus aku sampaikan.”
Andra menatap layar lama sekali. Hatinya berperang. Bagian dirinya ingin menolak, melarikan diri sejauh mungkin. Tapi bagian lain, bagian yang masih mencintai Nayla dengan sisa-sisa harapan, memaksa untuk pergi. Ia memilih bagian yang kedua.
Malam itu, mereka bertemu di café kecil tempat dulu mereka merayakan ulang tahun Nayla. Andra datang lebih dulu. Jantungnya berdegup kencang, seperti ingin meloncat keluar. Lalu Nayla muncul, masih dengan senyum yang sama—senyum yang dulu menjadi dunianya.
“Terima kasih sudah datang,” ucap Nayla pelan.
Andra hanya mengangguk. Suasana terasa canggung, tapi juga penuh pertanyaan yang mendesak untuk keluar. Sebelum Andra sempat bertanya, Nayla lebih dulu bicara.
“Aku… ingin minta maaf,” katanya, menunduk. “Semua yang terjadi… bukan salahmu. Aku yang salah. Aku yang menyerah terlalu cepat.”
Andra menatapnya dalam diam. Kata-kata itu menusuk, tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Ada sesuatu di mata Nayla. Sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya—sebuah ketakutan.
“Ada apa, Nay?” suara Andra bergetar.
Nayla menarik napas panjang, lalu menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. “Aku sakit, Dra. Dokter bilang… aku nggak punya banyak waktu lagi.”
Dunia Andra berhenti. Semua suara lenyap. Ia ingin bertanya apakah ini lelucon kejam, tapi melihat wajah Nayla, ia tahu ini nyata. Semua luka yang ia rasa seketika menguap, tergantikan rasa hancur yang tak terlukiskan.
“Aku nggak mau kamu tahu dengan cara ini,” Nayla melanjutkan, suaranya bergetar. “Aku menjauh karena nggak mau kamu ikut terluka. Aku ingin kamu bahagia tanpa harus menanggung ini.”
Air mata Andra jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini ia mengira dikhianati. Ia memupuk benci untuk melawan rindu. Tapi ternyata Nayla tidak pernah berhenti mencintainya—ia hanya berusaha melindunginya dari rasa sakit yang lebih besar.
Andra menggenggam tangan Nayla erat, seakan jika ia melepas, Nayla akan hilang selamanya. “Kamu bodoh,” suaranya parau. “Kalau kamu harus pergi, biar aku yang menemanimu sampai akhir. Jangan pernah hadapi ini sendiri.”
Nayla tersenyum tipis, dan di balik senyum itu, Andra melihat semua cinta yang selama ini ia ragukan. Malam itu, mereka menangis dalam diam, saling menggenggam erat, mencoba menghentikan waktu yang terus berlari.
Di luar, lampu kota berkelip seperti bintang jatuh. Andra tahu kisah mereka akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa dikutuk oleh cinta. Karena meski akhir itu menyakitkan, mereka akan menjalaninya bersama—sampai nafas terakhir.