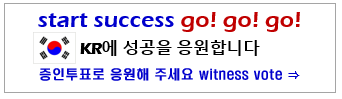Cerita Pendek | Rumah yang Tak Lagi Pulang
Selamat malam sahabat Steemit. Kalian sudah nonton film Ipar Adalah Maut? Jika iya, mungkin ada di antara kita yang merasakan bahwa film itu kurang memberikan pancingan yang mewmicu amarah penonton bukan? Setidaknya itu yang saya rasakan. Plot twistnya kurang greget, kurang memberikan daya hantam pada emosi penonton.
Andaikan penulis naskah membuat alur yang berbeda, pasti filmnya akan lebih seru. Kisah perselingkuhan dari dalam keluarga, merupakan hal yang jamak terjadi. Karena itu, menarik jika kelak ada film lain dengan cerita yang sama, tapi kisah akhir filmnya berbeda.
Saya mencoba menulis cerita pendek dengan kisah film itu. Kira-kira begini ceritanya.
Dina merasa sangat bahagia. Ia merasa menjadi perempuan yang paling bahagia di antara kerabat dan keluarga besarnya. Punya suami yang baik dan penyabar serta anak-anak yang cerdas dan lucu. Sejauh ini rumah itu selalu hangat. Tawa anak-anak menjadi melodi yang menghibur ruang tamu setiap sore. Dina, sesungguhnya hanya perempuan sederhana yang merasa hidupnya sempurna. Lebih lagi karena memiliki Arman, sosok yang ia kagumi sejak kuliah. Setia, sabar, penyayang.
Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga: Maya. Adik kandungnya sendiri. Maya datang setahun setelah Dina menikah. Katanya, untuk mencari kerja di kota. Dina bahagia. Rumah jadi ramai. Ia percaya keluarga harus saling menopang. Tapi sejak hari pertama, ia menangkap sesuatu yang aneh, sesuatu yang boleh disebut mencurigakan. Tatapan Maya ke arah Arman, bukan tatapan biasa. Dina sempat menepis prasangka itu. “Ah, aku cuma berlebihan,” batinnya. Ia percaya Arman. Ia percaya darah dagingnya sendiri.
Hari berganti bulan. Maya makin sering di rumah. Ia yang dulu pemalu, kini leluasa. Meminjam baju Dina, ikut memasak, bahkan duduk di sofa menonton film bersama Arman ketika Dina sedang mencuci. Dina tak ingin memperbesar masalah. Ia diam.
Sampai suatu malam. Dina terbangun. Jam menunjukkan pukul dua pagi. Ia menoleh ke samping, tempat Arman biasanya tidur. Kosong. Rasa dingin merayap ke dadanya. Ia keluar kamar. Langkahnya pelan, jantung berdegup keras. Suara tawa kecil terdengar dari dapur. Dina mendekat. Dan di sanalah ia melihatnya.
Arman dan Maya. Duduk berdampingan. Gelas kopi di meja. Wajah mereka terlalu dekat. Maya tertawa, tangan Arman menyentuh pipinya. Dunia Dina runtuh. Ia ingin berteriak. Tapi suara itu terkunci di tenggorokan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia kembali ke kamar. Malam itu, ia tidak tidur.
Esok paginya, Dina mencoba bersikap biasa. Ia memasak sarapan, mengantar anak ke sekolah. Tapi hatinya porak-poranda. Ia tidak bisa menatap Arman seperti dulu. Tidak bisa memeluk anak-anak tanpa rasa bersalah. Ia ingin marah, tapi ia memilih diam.
Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Maya semakin berani. Bahkan di depan mata Dina, ia bersikap manja pada Arman. Dina hanya bisa menahan. Sampai akhirnya ia tidak tahan lagi.
Sore itu, Dina menunggu Arman pulang. Maya sedang keluar. Saat pintu terbuka, Dina langsung menatap suaminya.
“Kita harus bicara,” suaranya bergetar.
Arman terdiam, lalu menghela napas. Seolah tahu apa yang akan dibicarakan.
“Dina, maafkan aku,” ucapnya pelan.
Dina menangis. Kata itu cukup jadi pengakuan. Semua runtuh.
“Kenapa, Man? Apa aku kurang? Apa kamu nggak bahagia sama aku?” suaranya pecah.
Arman menggeleng. “Bukan itu. Aku… aku nggak tahu kenapa. Semua terjadi begitu saja.”
Jawaban yang paling menyakitkan. Ia memilih diam. Air mata yang bicara.
Malam itu, Dina mengambil keputusan. Ia akan pergi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak sanggup. Ia berkemas diam-diam. Mengajak anak-anak ikut. Ia ingin menjauh dari luka ini.
Tapi takdir punya rencana lain.
Ketika Dina mengemasi pakaian, pintu kamar terbuka. Maya berdiri di sana. Wajahnya pucat. Di tangannya, ada koper kecil.
“Aku mau pergi, Kak,” ucap Maya lirih.
Dina menatapnya tajam. “Pergi? Setelah kamu hancurkan rumah tangga aku?”
Air mata Maya jatuh. “Aku salah. Aku... hamil.”
Dina terdiam. Dunia berhenti. Kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun.
“Apa?” suaranya hampir tak terdengar.
Maya menunduk, bahunya bergetar. “Aku hamil, Kak. Dari Abang.”
Dina jatuh terduduk. Nafasnya terputus-putus. Ia ingin marah, ingin menampar, tapi tubuhnya lemas. Segalanya gelap.
Beberapa menit kemudian, Arman datang. Wajahnya pucat. “Dina, biar aku jelasin—”
“Keluar!” teriak Dina. Suaranya pecah, histeris. Anak-anak berlari dari kamar sebelah, menangis melihat ibunya.
Arman mendekat. “Dina, aku salah. Tapi jangan pergi. Aku akan tanggung jawab. Aku akan nikahi Maya—”
Tamparan keras mendarat di pipi Arman. Dina menatapnya dengan mata basah. “Kamu... penghianat. Dan kamu, Maya... aku nggak punya adik lagi.”
Malam itu, Dina pergi. Dengan anak-anak. Tanpa sepatah kata lagi.
Lima tahun kemudian.
Dina duduk di sebuah kafe kecil. Ia tampak lebih dewasa, lebih kuat. Di hadapannya, dua anaknya tertawa. Mereka tumbuh tanpa ayah. Tapi Dina bahagia melihat mereka baik-baik saja.
Tiba-tiba, seseorang masuk. Langkahnya gontai, wajahnya tirus. Arman.
Dina terpaku. Arman mendekat, duduk tanpa izin. “Dina… kabarku nggak baik.”
Dina menatapnya datar. “Kenapa kamu ke sini?”
Arman menghela napas. “Maya… dia meninggal. Dua tahun lalu. Kanker. Anakku… anak kita, sekarang di panti.”
Air mata Dina jatuh, meski ia tak ingin. Semua amarah seolah hilang diganti perih yang lain. Ia membayangkan Maya, adik yang dulu ia peluk setiap malam, kini tinggal nama.
Arman menunduk. “Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma… mau bilang maaf. Aku hancurin semua.”
Dina menatapnya lama. Ada rasa benci, tapi juga iba. Ia menarik napas panjang. “Kamu benar, Man. Kamu hancurkan semuanya. Tapi… hidup terus jalan.”
Ia bangkit, menggandeng anak-anaknya, lalu pergi.
Di luar kafe, hujan turun deras. Dina mendongak ke langit. Ia tak tahu apa namanya perasaan ini. Lega? Sedih? Entahlah. Yang ia tahu, hatinya akhirnya bebas.
Nah kira-kira, kalau seperti akhirnya, akan memberikan plot twist yang lebih menghantam, bukan?